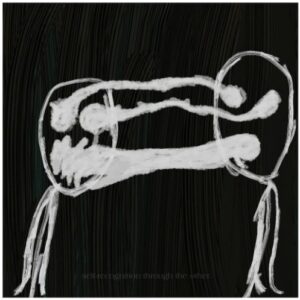“Tak ada bedanya apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu.
Maka, buatlah proyek spektakuler[1], seperti Nuh.“
Keresahan manusia modern terhadap “apa yang dipikirkan orang lain” bukanlah sekadar kecemasan sosial biasa; ini adalah jejak purba dari moralitas kawanan (Herdenmoral) yang telah mendarah daging. Dalam kerangka Nietzschean, keinginan untuk diterima dan divalidasi oleh publik adalah gejala dekadensi yang paling banal—sebuah pelemahan vitalitas di mana individu mengizinkan dirinya menjadi objek bagi subjek kolektif yang medioker.
Ketika seseorang mendasarkan tindakannya pada ekspektasi publik, ia tidak hanya sedang melakukan pengkhianatan terhadap Will to Power (Kehendak untuk Berkuasa), tetapi juga meniadakan kemungkinan Will to Power itu muncul. Namun di titik ini, perlu kehati-hatian: sebab, Will to Power itu sendiri dapat berubah menjadi berhala baru jika diperlakukan sebagai legitimasi otomatis bagi setiap dorongan batin. Tidak semua yang lahir dari “insting” adalah afirmasi kehidupan; sebagian hanyalah reaksi yang belum menemukan lawannya. Mengkultuskan kehendak personal tanpa mengujinya pada resistensi dunia berisiko mengganti moralitas kawanan dengan mitologi individual yang sama tertutupnya.
Premis “Tak ada bedanya apa yang dipikirkan orang lain…” bukanlah nasihat pengembangan diri, melainkan sebuah proklamasi Kematian Penonton. Tidak ada penonton yang layak dipertimbangkan, karena tidak ada satu pun dari mereka yang akan menanggung konsekuensi hidupmu.
Dalam penciptaan sesuatu yang benar-benar berbeda (spektakuler), sang kreator harus terlebih dahulu membunuh “Tuhan”, yang dalam konteks ini, berbentuk opini publik. Tetapi tindakan membunuh “Tuhan” tidak menjamin lahirnya kebenaran. Sebab dalam banyak kasus, yang tersisa hanyalah ruang kosong tempat kesalahan tumbuh tanpa koreksi. Sehingga tidak semua yang dicemooh publik sedang mendahului zamannya; sebagian hanya salah membaca medan, dan kesalahan itu tidak otomatis menjadi kebajikan hanya karena dilakukan sendirian.
Tanpa keberanian untuk menjadi “yang jahat” atau “yang gila” di mata massa, seseorang hanya akan mampu menghasilkan reproduksi dari apa yang sudah aman beredar, bukan kreasi. Dalam konteks ini, Nuh muncul sebagai metafora ekstrem bagi autarki estetika, suatu kondisi di mana kebenaran sebuah karya tidak lagi bergantung pada konsensus, melainkan pada ketetapan batin sang arsitek. Tindakan Nuh membangun bahtera di tengah gurun adalah sebuah tindakan yang secara fungsionalitas dianggap absurd oleh logika sezamannya. Namun, ketidakpedulian terhadap ejekan tetangganya bukanlah bentuk kenaifan, melainkan bentuk Kedaulatan. Ia telah melampaui “kebenaran pasar”. Melampaui kebutuhan untuk dimengerti.
Proyek spektakuler menuntut isolasi radikal dan periode di mana sang pencipta harus menjadi tuli—bukan terhadap kritik yang buruk saja, tetapi juga terhadap pujian yang prematur—agar bisa mendengar suara instingnya sendiri. Namun ketulian ini bukan keadaan permanen. Isolasi yang terlalu lama berisiko mengeras menjadi dogma privat. Insting yang tidak pernah diuji dapat kehilangan ketajamannya kemudian berubah menjadi gema dirinya sendiri. Di titik ini, kesendirian tidak lagi produktif—ia akan menjadi steril.
Kebebasan dari penilaian orang lain bukanlah sebuah sikap pasif, melainkan sebuah prasyarat teknis bagi lahirnya Magnum Opus. Jika Nuh mendengarkan kritik tentang “efisiensi lokasi” atau “estetika kapal”, bahtera itu tidak akan pernah sanggup menanggung beban badai yang akan datang.
Setiap proyek spektakuler pada hakikatnya adalah sebuah bahtera—sebuah struktur yang dibangun untuk bertahan melampaui keruntuhan zamannya. Sebuah upaya individual untuk tidak ikut tenggelam bersama kebiasaan umum. Nietzsche berbicara tentang Umwertung aller Werte atau penilaian kembali atas semua nilai, dan sebuah proyek spektakuler tidaklah melayani dunia yang sekarang; ia justru menubuatkan kehancuran tatanan lama.
Ketidakpedulian terhadap opini orang lain adalah pengakuan pahit bahwa dunia mereka sudah “tenggelam” dalam dekadensi pikiran mereka sendiri, jauh sebelum hujan pertama turun. Namun pengakuan ini tetap harus berani menanggung kemungkinan paling tidak nyaman: bahwa mungkin air bah tidak datang sesuai perkiraan, atau datang dengan arah yang tak terduga. Proyek spektakuler yang matang bukan hanya siap menertawakan dunia tapi juga siap menghadapi kemungkinan bahwa dunia akan menertawakannya dengan alasan yang sah.
Oleh karena itu, membangun proyek spektakuler merupakan tindakan politik yang radikal: sebuah penolakan untuk berpartisipasi dalam keruntuhan kolektif dan memilih untuk mengapung dalam kebenaran yang diciptakan sendiri.
Pada akhirnya, proyek spektakuler adalah ujian ketahanan psikologis seseorang terhadap kesepian yang mendalam. Hanya mereka yang mampu menanggung beban “menjadi asing” yang berhak atas masa depan. Kita tidak membangun untuk mendapatkan tepuk tangan, karena tepuk tangan adalah mata uang dari mereka yang kita tinggalkan di daratan yang akan tenggelam.
Maka, palulah kayu-kayumu. Biarkan setiap paku yang kau tancapkan menjadi paku mati bagi pengaruh opini publik terhadap jiwamu. Jadilah Nuh bagi dirimu sendiri: seorang arsitek yang kedinginan dan ditertawakan, namun memegang kunci bagi apa yang akan tetap tegak ketika semua yang lumrah musnah ditelan air bah sejarah.
[1] Proyek spektakuler adalah apa pun yang saat ini kita takuti untuk mulai karena kita terlalu sibuk membayangkan wajah sinis orang lain.